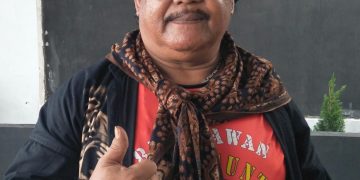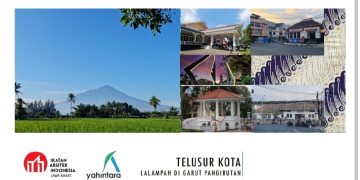oleh : Galih F. Qurbany, Pengamat Kebijakan dan Informasi Strategis, Wakil Ketua KADIN Kab Garut.
Kebijakan perdagangan proteksionis yang diusung Donald Trump melalui pajak timbal balik (reciprocal tax) bukan sekadar ancaman abstrak, melainkan bom waktu yang dapat meledak dan mengguncang industri ekspor Indonesia. Jika kebijakan ini kembali diterapkan, sektor tekstil dan pakaian jadi Indonesia akan menjadi korban pertama. Amerika Serikat adalah salah satu pasar utama bagi produk-produk ini, dan penerapan tarif tinggi akan langsung menghantam daya saing Indonesia di pasar global.
Penerapan pajak timbal balik secara sepihak akan menaikkan harga produk tekstil dan pakaian Indonesia di pasar AS, membuatnya kalah bersaing dengan negara lain yang memiliki perjanjian dagang khusus dengan AS. Hal ini akan berujung pada penurunan volume ekspor yang signifikan. Bagi industri yang menyerap jutaan tenaga kerja, dampak ini bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi, tetapi realitas pahit yang akan menimpa ribuan buruh, pabrik-pabrik yang gulung tikar, dan ekonomi daerah yang terpuruk.
Selain ancaman dari pajak timbal balik, pelemahan kurs rupiah yang terus terjadi akan semakin memperparah situasi. Biaya produksi di sektor tekstil dan pakaian sangat bergantung pada impor bahan baku, seperti kapas dan bahan kimia untuk pewarnaan. Dengan melemahnya rupiah terhadap dolar AS, harga bahan baku akan melonjak, menyebabkan biaya produksi meningkat secara signifikan. Hal ini semakin menggerus daya saing industri dalam negeri karena harga produk menjadi lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor dari negara lain. Jika tidak ada intervensi yang tepat, banyak pelaku usaha akan terjebak dalam dilema antara menaikkan harga yang berisiko kehilangan pasar atau mempertahankan harga dengan margin keuntungan yang makin tipis.
Dampak dari kombinasi pajak timbal balik dan pelemahan rupiah adalah potensi ledakan pengangguran di sektor ini. Jika ekspor menurun drastis, industri tekstil dan pakaian jadi tidak akan mampu mempertahankan jumlah tenaga kerja yang ada. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran menjadi ancaman nyata, terutama di sentra-sentra industri seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bukan hanya buruh pabrik yang terdampak, tetapi juga sektor pendukung seperti transportasi, logistik, dan perdagangan bahan baku. Dalam skenario terburuk, pengangguran massal ini bisa memicu efek domino berupa meningkatnya angka kemiskinan dan ketidakstabilan sosial.
Dampak ini juga akan sangat terasa di Kabupaten Garut, yang merupakan salah satu sentra industri alas kaki terbesar di Indonesia. Banyak pabrik sepatu global, termasuk yang memproduksi merek-merek terkenal seperti Nike, beroperasi di Garut dan sangat bergantung pada ekspor ke pasar AS dan Eropa. Jika pajak timbal balik diterapkan dan rupiah terus melemah, biaya produksi yang melonjak akan mengancam keberlanjutan industri ini. Penurunan pesanan dari luar negeri bisa berujung pada PHK massal bagi ribuan pekerja di sektor sepatu dan alas kaki, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Garut.
Selain industri sepatu, Garut juga memiliki sektor produk kulit Sukaregang yang telah berhasil menembus pasar ekspor, khususnya ke Eropa. Produk kulit dari Sukaregang dikenal memiliki kualitas tinggi dan telah menjadi andalan ekspor. Namun, dengan semakin ketatnya persaingan global akibat kebijakan proteksionisme, produk kulit Garut bisa kehilangan daya saingnya. Jika pemerintah tidak segera melakukan intervensi, industri ini bisa mengalami kemunduran yang signifikan, merugikan para pengusaha dan pekerja lokal yang telah lama mengandalkan sektor ini sebagai mata pencaharian.
Yang lebih mengkhawatirkan, kebijakan pajak timbal balik Trump ini juga melanggar berbagai regulasi perdagangan internasional. Pengenaan tarif secara sepihak tanpa konsultasi dengan mitra dagang bertentangan dengan prinsip-prinsip World Trade Organization (WTO) yang mengatur perdagangan bebas dan adil. Selain itu, kebijakan ini juga merusak komitmen Amerika Serikat dalam perjanjian perdagangan seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan berbagai kesepakatan bilateral yang seharusnya melindungi kepentingan negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Indonesia terkena tarif impor (resiprokal) sebesar 32%, yang merupakan kedua tertinggi di ASEAN setelah Vietnam dengan 46%, serta keempat secara global setelah Kamboja (49%) dan China (34%). Padahal, AS adalah pasar ekspor terbesar bagi Indonesia dengan produk andalan seperti tekstil, sepatu, elektronik, dan produk karet yang bernilai miliaran dolar. Kebijakan Trump ini secara langsung mempersulit daya saing ekspor Indonesia, memberikan keuntungan bagi negara-negara yang memiliki tarif lebih rendah, dan membuat Indonesia kehilangan pangsa pasar penting.
Trump bahkan menjuluki kebijakan resiprokal ini sebagai “Hari Pembebasan” pada tanggal 3 April, menandakan langkah besar AS untuk mengurangi defisit perdagangannya dengan berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, bagi Indonesia, ini bukan pembebasan, melainkan ancaman serius terhadap sektor industri yang selama ini menopang jutaan tenaga kerja.
Jika kebijakan ini diterapkan tanpa perlawanan diplomatik yang kuat, Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya akan semakin terpinggirkan dalam sistem perdagangan global. AS akan menggunakan dominasinya untuk menekan negara-negara lain tanpa konsekuensi yang berarti. Oleh karena itu, Indonesia harus segera membawa masalah ini ke forum internasional, termasuk WTO dan ASEAN, untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak diterapkan secara sewenang-wenang dan melanggar aturan perdagangan global.
Namun, yang perlu dicatat, Indonesia sendiri secara umum tidak menerapkan kebijakan resiprokal, sehingga produk impor masih membanjiri pasar domestik tanpa hambatan yang signifikan. Hal ini membuat industri dalam negeri semakin tertekan karena harus bersaing dengan produk asing yang sering kali memiliki harga lebih murah. Tanpa kebijakan proteksi yang memadai, industri tekstil, alas kaki, dan produk kulit akan semakin terhimpit oleh serbuan barang impor.
Meski demikian, Indonesia telah menerapkan kebijakan resiprokal pada produk-produk tertentu, terutama yang berkaitan dengan sektor strategis. Namun, kebijakan ini belum cukup untuk melindungi industri lokal secara luas. Pemerintah harus segera mengkaji ulang kebijakan perdagangan yang lebih seimbang agar tidak hanya menjadi pasar bagi negara lain, tetapi juga mampu mempertahankan daya saing industri dalam negeri.
Indonesia tidak boleh hanya berdiam diri menghadapi ancaman ini. Pemerintah harus segera melakukan langkah diplomasi ekonomi yang agresif untuk menegosiasikan tarif yang lebih adil dengan AS. Ketergantungan pada satu pasar harus dihentikan. Indonesia perlu bergerak cepat dengan memperluas ekspor ke pasar non-tradisional seperti Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Diversifikasi pasar bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Indonesia juga harus mencari negara-negara baru di luar Amerika Serikat sebagai tujuan ekspor. Diversifikasi ekspor ke negara-negara lain tanpa bergantung secara berlebihan kepada pasar AS harus menjadi agenda utama kebijakan perdagangan nasional. Ini tidak hanya sebagai bentuk mitigasi risiko, tetapi juga menjadi peluang strategis untuk memperluas jaringan dagang global Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India, China), baik dalam penguatan modal, investasi, maupun dalam membangun kerjasama perdagangan yang lebih intensif dan seimbang.
Dampak dari kebijakan proteksionisme AS bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ini adalah tantangan besar yang membutuhkan respons cepat dan tepat. Jika Indonesia gagal mengantisipasi, maka konsekuensinya adalah gelombang PHK massal, runtuhnya sektor industri, dan ketidakstabilan ekonomi yang berkepanjangan. Namun, jika langkah strategis segera diambil, Indonesia masih punya peluang untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga memperkuat posisinya di perdagangan global. Pertanyaannya, apakah kita siap bergerak atau hanya akan menunggu kehancuran datang?.***