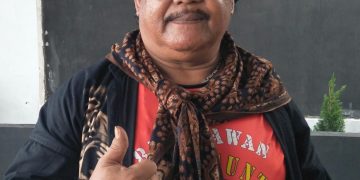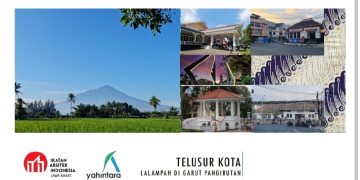Oleh: Galih F. Qurbany.
(Wakil Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut, DKKG )
Seperti tahun-tahun sebelumnya, tanggal 21 April kembali diperingati sebagai Hari Kartini. Panggung-panggung seremoni dihias dengan kebaya, parade anak-anak sekolah, dan lantunan puisi tentang emansipasi perempuan. Poster Kartini kembali muncul di ruang-ruang publik, lengkap dengan kutipan *_“Habis Gelap Terbitlah Terang.”_* Semuanya terasa sakral, nyaris seperti ritual tahunan yang tidak boleh dilanggar. Tapi dalam gegap gempita perayaan ini, sejarah seperti menelan ludahnya sendiri.
Di tanah Garut yang sejuk, jauh sebelum nama Kartini diteriakkan dalam ruang-ruang sekolah, telah berdiri seorang perempuan pelopor. Namanya Raden Ayu Lasminingrat. Lahir pada tahun 1854, ia tumbuh dalam suasana intelektual keluarga bangsawan Sunda yang progresif. Pada usia 9 hingga 12 tahun, Lasminingrat diasuh oleh pasangan Belanda—Levyson Norman dan istrinya—yang membawanya ke Sumedang untuk diberikan pendidikan ala Barat. Niatnya bukan menjadikan Lasminingrat alat kolonial, tapi jembatan antara dunia modern dan budaya lokal.
Bandingkan dengan Raden Ajeng Kartini, yang lahir dua puluh lima tahun kemudian, pada tahun 1879, dan meninggal muda pada usia 25 tahun pada 1904. Kartini memang dikenal karena surat-suratnya kepada sahabat Belandanya, yang kemudian dihimpun dalam buku Door Duisternis tot Licht (“Habis Gelap Terbitlah Terang”). Namun surat-surat ini baru diterbitkan secara luas setelah kematiannya, dan dampaknya bersifat simbolik, lebih banyak menginspirasi kalangan elite daripada memberi efek riil pada perubahan sistemik pendidikan perempuan.
Sementara Dewi Sartika, yang lahir di Bandung pada tahun 1884 dan wafat tahun 1947, secara historis memang berjasa dalam mendirikan sekolah perempuan di Jawa Barat. Tapi, yang sering dilupakan publik adalah: Dewi Sartika adalah murid ideologis dan kultural dari Lasminingrat. Ia meneruskan apa yang sudah dirintis oleh Lasminingrat di Garut sejak dua dekade sebelumnya.
Lasminingrat bukan sekadar ningrat. Ia intelektual sejati. Perempuan pertama dari Priangan yang menguasai bahasa Belanda secara fasih. Ia menerjemahkan karya-karya sastra moral dan pedagogis dari Eropa ke dalam bahasa Sunda agar bisa dibaca oleh rakyat jelata. Beberapa karyanya antara lain *Carita Erman* (_terjemahan dari Erman’s Lebensgeschichte_), *Warnasari atawa Riwajatna Poetra Sarekat*, serta adaptasi dari _Gedachten over de opvoeding karya Christoph von Schmid_. Ia tidak hanya menerjemahkan, tapi mentransformasikan nilai-nilai pencerahan kepada perempuan Sunda melalui bahasa ibu mereka—dengan sentuhan moral dan lokalitas yang membumi. Sekolah yang ia dirikan, *_Sekolah Keutamaan Istri_*, bukan sekadar tempat belajar, tetapi basis gerakan pencerahan perempuan bumiputra.
Ironisnya, ia justru dilupakan. Namanya tercecer dari buku-buku pelajaran. Sejarah formal lebih senang merayakan simbol daripada substansi. Bahkan, fakta sejarah mencatat: Dewi Sartika yang kini dikenang sebagai pelopor pendidikan perempuan di Jawa Barat adalah murid, penerus, sekaligus ‘buah’ dari gagasan Lasminingrat.
Salah satu alasan yang kerap disodorkan mengapa ia tidak diakui setara dengan Kartini adalah karena ia dianggap “terlalu dekat dengan Belanda.” Tapi siapa yang tidak, dalam konteks zaman itu? Bahkan Kartini sendiri mendapatkan fasilitas pendidikan karena relasi ayahnya sebagai Bupati Jepara dengan administrasi kolonial. Ini bukan soal afiliasi, tapi soal bagaimana seseorang memanfaatkan ruang kolonial untuk membuka jalan kebebasan bagi bangsanya.
Sejarah bangsa ini, sayangnya, tak selalu ditulis oleh mereka yang mencintai kebenaran. Ia sering kali ditulis oleh penguasa masa lalu, atau oleh narasi resmi yang lebih menyukai cerita-cerita yang bisa dijual dan mudah dicerna. Kartini dengan surat-suratnya yang lembut, puitik, dan aman dari kontroversi lebih mudah untuk diperingati. Dewi Sartika, dengan narasi nasionalisme yang kompatibel dengan konstruksi negara, lebih gampang diterima. Tapi Lasminingrat? Terlalu kompleks, terlalu cerdas,