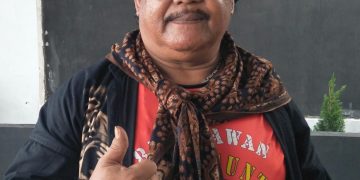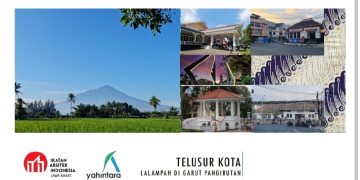Usulan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Lahir ke-60 Partai Golkar untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memicu perdebatan panas. Sejak Reformasi 1998, Indonesia mengadopsi sistem pemilihan langsung yang memberikan rakyat kesempatan untuk memilih pemimpin mereka. Namun, usulan ini mempertanyakan kembali relevansi demokrasi langsung, dengan dalih efisiensi anggaran dan stabilitas politik.
Menurut Galih F. Qurbany, Direktur Pusat Kajian dan Inovasi Strategis (PAKIS), gagasan ini membawa risiko besar terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemilihan melalui DPRD memiliki potensi melemahkan kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi utama demokrasi. “Secara teori, demokrasi langsung lahir dari upaya memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat secara aktif dalam menentukan nasib mereka. Jika pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD, kita justru mundur ke model demokrasi perwakilan yang telah terbukti bermasalah di banyak negara,” ujarnya.
Galih mengutip teori partisipasi politik dari Carole Pateman yang menekankan pentingnya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan. Demokrasi perwakilan sering kali menciptakan jarak antara rakyat dan elite politik, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan kehendak masyarakat. Hal ini diperburuk dengan potensi korupsi dan kolusi dalam pemilihan oleh anggota DPRD, yang membuka peluang untuk praktik “jual beli suara.”
Secara historis, beberapa negara yang kembali menerapkan sistem demokrasi perwakilan justru mengalami kemunduran demokrasi dan kegagalan tata kelola. Salah satu contoh mencolok adalah Thailand, yang pada 2014 mengalami transisi dari demokrasi langsung ke model demokrasi yang lebih terkonsolidasi di tangan elite militer. Mekanisme perwakilan diperketat melalui Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO), yang mengatur pemilihan pejabat melalui sistem yang sangat elitis. Dampaknya, negara tersebut menghadapi krisis legitimasi yang berkepanjangan, ditandai dengan protes massal, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, dan stagnasi ekonomi.
Hungaria juga menjadi contoh negara yang bergerak ke arah demokrasi perwakilan yang lebih terkendali oleh elite. Reformasi pemilu di bawah pemerintahan Viktor Orbán memusatkan kekuasaan pada partai-partai tertentu, mengurangi keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Akibatnya, Hungaria kini dicap sebagai negara dengan demokrasi iliberal, di mana transparansi, akuntabilitas, dan keadilan politik semakin terkikis.
Galih juga menggarisbawahi bahwa perubahan sistem seperti ini sering kali dimanfaatkan oleh oligarki politik untuk memperkuat dominasi mereka. “Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka proses pemilu akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan elite politik lokal. Ini membuka jalan bagi kekuasaan oligarki yang sulit diintervensi oleh rakyat biasa,” tegasnya. Ia mengingatkan bahwa situasi serupa pernah terjadi di era Orde Baru, di mana pemilihan melalui DPRD lebih mencerminkan kepentingan politik pusat daripada kehendak rakyat di daerah.
Di sisi lain, Galih tidak menafikan kelemahan sistem pemilihan langsung yang saat ini diterapkan di Indonesia, seperti tingginya biaya politik dan polarisasi masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa solusi untuk masalah ini bukanlah dengan kembali ke sistem lama, melainkan memperbaiki tata kelola demokrasi langsung. Ia mengusulkan penggunaan teknologi untuk menekan biaya pemilu, memperketat regulasi dana kampanye, dan meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu sebagai alternatif yang lebih progresif.
Konteks Indonesia juga perlu diperhatikan. Dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya yang tinggi, keterlibatan rakyat dalam demokrasi langsung menjadi penting untuk menjaga rasa memiliki terhadap sistem politik. Demokrasi perwakilan yang terpusat pada DPRD justru berisiko memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, karena rakyat kehilangan akses langsung dalam menentukan pemimpin mereka.
Pelajaran dari negara-negara lain menunjukkan bahwa kembali ke demokrasi perwakilan bukanlah solusi ideal untuk mengatasi tantangan demokrasi. Sebaliknya, pendekatan seperti itu cenderung menciptakan krisis legitimasi, memperkuat oligarki, dan melemahkan kontrol rakyat terhadap kekuasaan. Di tengah upaya Indonesia untuk memperkuat demokrasi, langkah seperti ini dapat dianggap sebagai kemunduran yang mengancam pencapaian Reformasi 1998.
Galih menutup dengan peringatan tegas bahwa demokrasi adalah proses yang terus berkembang dan membutuhkan penyesuaian, bukan kemunduran. “Kita harus belajar dari sejarah, baik dari pengalaman kita sendiri maupun dari negara lain. Demokrasi langsung memang mahal dan penuh tantangan, tetapi itu adalah harga yang harus kita bayar untuk menjaga kedaulatan rakyat. Jika kita ingin demokrasi kita bertahan, kita harus mencari cara untuk memperbaikinya, bukan menghapusnya,” pungkasnya.***